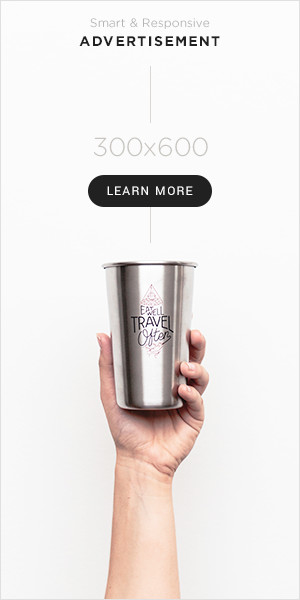Matahari siang di Riangpuho menggantung nyaris tanpa bayangan. Terik menyengat, tapi ada yang lebih panas dari itu—ketakutan yang datang tanpa aba-aba. Tanah bergoyang hebat, menggeliat seperti ular raksasa yang bangkit dari tidur panjang. Dalam sekejap, gempa bumi mengguncang pesisir Flores. Gelombang besar menyusul, melahap daratan tanpa ampun.
Itu terjadi pada tahun 1992.
Hari itu, Hironimus Raga Aran—lebih akrab disapa Hery—masih seorang bocah. Namun, kenangan tentang tsunami itu tak pernah mengecil seiring waktu. Lima nyawa hilang dari kampungnya di Riangpuho, termasuk sang kakek dan empat keponakan yang tinggal tak jauh dari garis pantai. Hanya sang nenek yang selamat karena ia berada beberapa meter lebih jauh dari laut.
“Saya masih kecil, tapi saya ingat betul… jeritan, deru air, dan tubuh-tubuh yang hilang,” kenang Hery dengan suara pelan. Kalimat itu seperti upaya menjaga luka lama agar tak menganga kembali.
Dari Ladang ke Sekolah, dari Mimpi ke Kenyataan
Hery lahir pada 24 Maret 1984, dari keluarga petani sederhana yang hidup berpindah dari kebun ke kebun. Dari Pantai Painhaka ke Lewo Lebao, hingga akhirnya menetap di Riangpuho saat ia berusia tujuh tahun. Ia tumbuh dalam kerasnya alam dan sempitnya pilihan, tapi juga ditempa oleh nilai kerja keras, ketekunan, dan harapan.
Setamat SDN Lebao Tanjung tahun 1997, ia melanjutkan ke SMP Pati Beda Lewokluok (kini SMP Negeri 1 Demon Pagong), lalu ke SMEA Lamaholot. Di kampung tempat ia tumbuh, tak banyak anak yang mampu bertahan di jalur pendidikan. Namun Hery berbeda. Ia tak ingin jadi besar, ia ingin berguna.
Ia sempat bekerja di Mataram, lalu mencoba kuliah di Universitas Nusa Nipa Maumere. Tapi hidup tak selalu memberi ruang untuk impian. Setelah menikah pada 2008, ia terpaksa berhenti kuliah dan pulang ke Waibao. Ia menjadi petani, menanam harapan di tanah sendiri.
Namun tekanan ekonomi membuatnya kembali menimbang langkah. Tahun 2011, ia merantau ke Kalimantan, bekerja di perusahaan pengeboran batu bara. Di sela pekerjaan, ia membangun usaha bengkel las kecil bernama Aran88—sebuah doa dalam bentuk nama: semoga hidup dan semangatnya tetap menyala seperti api las yang menghubungkan besi.
Tiga tahun merantau cukup bagi Hery untuk menabung dua hal: modal dan keyakinan. Ia pulang ke Larantuka. Ia mendirikan bengkel las, dan dari sana, perlahan menyusun mimpi: membangun tanah kelahirannya sendiri—Waibao.
“Waibao harus berubah”
Tahun 2021, Hery mengambil keputusan besar: mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Waibao. Bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena sebuah keyakinan.
“Sebelum masuk ke pemerintahan, saya selalu bermimpi bahwa Waibao ini harus berubah, dan perubahan itu harus terlahir dari ide saya,” ujarnya mantap.
Kemenangannya bukan sekadar hasil pemilihan, tapi simbol keberhasilan seorang anak desa yang berangkat dari nol—yang kehilangan keluarga karena tsunami, pernah gagal kuliah, dan jatuh bangun dalam hidup.
Sebagai kepala desa, Hery memulai dari hal-hal sederhana tapi berdampak: sistem air bersih, akses jalan ke kebun, taman baca, kebun hortikultura, demplot jagung, dan kemitraan dengan BUMDes untuk menyerap hasil pertanian warga.
Perlahan, Waibao yang dulu tenang dan nyaris beku mulai bergerak. Tapi di balik semua upaya itu, hidup tak pernah sepenuhnya mulus.

Luka yang jadi pelajaran
Tahun 2024 menjadi babak kelam. Hery bersama dua aparat desa dan satu warga lain terjerat kasus dugaan penganiayaan. Proses hukum berjalan, dan pada 14 April 2024, mereka dijatuhi hukuman empat bulan penjara.
Hery tidak membela diri.
“Saya salah. Saya betul-betul merasa bersalah. Ini pelajaran. Jalan Tuhan untuk saya menjadi pemimpin yang lebih bijak,” katanya tanpa ragu. Tak ada pembelaan. Yang ada hanya kejujuran dan kesediaan belajar dari kesalahan.
Empat bulan di balik jeruji menjadi masa perenungan. Ia memahami bahwa kepemimpinan bukan soal kuasa, melainkan soal nilai—tentang sabar, tentang menghormati, dan tentang menghindari kekerasan dalam bentuk apapun.
Dari Luka, Tumbuh Tekad Baru
Kini, setelah menjalani masa hukuman, Hery kembali ke Waibao. Ia masih kepala desa. Masih Hery yang sama—bocah dari kebun, saksi tsunami, petani, perantau, dan kini pemimpin.
Waibao hari ini berbeda. Banyak yang telah berubah, namun Hery tahu: perubahan sejati tak hanya tampak pada infrastruktur, tapi terutama pada cara berpikir warganya.
“Saya harus melakukan sesuatu yang maksimal. Harus ada langkah maju,” katanya penuh keyakinan.
Dan mungkin, dari luka dan kejatuhan itulah, muncul sosok pemimpin yang lebih manusiawi. Lebih jujur. Lebih kuat. Di tangan Hery, Waibao bukan sekadar bergerak. Ia melangkah. Satu langkah lebih maju.
Penulis: Adi Antonius/Ypps. Editor: SP Pati Hokor/ Ypps